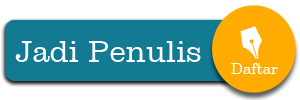Kabar dari Rembang (Sendhon Waton)
jujum18.21islam laknatan, islam rahmatan, jagad jawa, jawa news, maiyah cak nun, sendhon waton
Tidak ada komentar

Menghadiri sebuah acara obrolan adalah kesukaan saya. Entah
itu obrolan berkualitas, obrolan tak berkualitas, omong kodok, hingga omongan
percil saya suka, asalkan ada waktu luang atau waktu mirunggan. Seperti kemarin
tanggal 26 Maret 2017 saya datang ke sebuah acara obrolan yang diadakan oleh
Sanggar Cakraningrat di Rembang. Sanggar ini diprakarsai oleh seorang dalang
muda berbakat yang baru naik daun, yaitu Ki Sigid Ariyanto.
Asal-usul dan Golongan Tembang Jawa (Versi Mardawa Lagu)
jujum03.33Asal-usul tembang jawa, jagad jawa, mardawa lagu, seni jawa, seni karawitan, tembang jawa, tembang macapat
Tidak ada komentar

Tembang di Jawa memang kurang populer di kalangan manusia modern
sekarang ini. Mayoritas mereka hanya mengenal tembang macapat, padahal
tembang macapat ini adalah tembang cilik. Adapun tembang-tembang
lainnya yaitu, ada tembang Maca-sa Lagu, Maca-ro Lagu kemudian ada
Maca-tri Lagu dan yang terakhir adalah tembang Maca-pat Lagu.
Pencipta Nama Hari Jawa (Versi Wayang)
jujum14.54asal usul nama hari jawa, cerita wayang, hari jawa, jagad jawa, pencipta nama hari jawa, seni jawa, seni pedalangan
1 komentar

 Setelah mengetahui asal-usul nama hari di Jawa (baca: Nama Hari di Jawa) yang ternyata
adalah nama-nama Planet. Mari kita telusuri siapa pencetus nama-nama hari tersebut. Tentu ada yang kasih nama kan,
beberapa sumber yang Jagad Jawa baca, memang belum ada sejarah yang pasti,
namun ada beberapa cerita gotek atau tradisi lesan yang berkembang dan diyakini
hingga sekarang. Soal kebenaranya tentu masih dipertanyakan. Namun yang jelas
jangan diperdebatkan panjang lebar ya, nanti kita lengah dan hanya udur saja ga
bisa ngliwet, dan kendhilnya jadi nggoling.
Setelah mengetahui asal-usul nama hari di Jawa (baca: Nama Hari di Jawa) yang ternyata
adalah nama-nama Planet. Mari kita telusuri siapa pencetus nama-nama hari tersebut. Tentu ada yang kasih nama kan,
beberapa sumber yang Jagad Jawa baca, memang belum ada sejarah yang pasti,
namun ada beberapa cerita gotek atau tradisi lesan yang berkembang dan diyakini
hingga sekarang. Soal kebenaranya tentu masih dipertanyakan. Namun yang jelas
jangan diperdebatkan panjang lebar ya, nanti kita lengah dan hanya udur saja ga
bisa ngliwet, dan kendhilnya jadi nggoling.Kabar Dari Kayen
jujum09.00gangsaran, jagad jawa, jawa news, kabar dari kayen, penemuan di kayen, penemuan situs candi kayen
Tidak ada komentar

 JAGAD JAWA, Kabupaten Pati, memiliki sekitar 21 kecamatan, salah satunya
adalah Kecamatan Kayen. Letak kecamatan ini adalah berjarak dari pusat kota
Pati sekitar 17 Km. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sukolilo, sebelah
utara ada kabupaten Kudus dan Kecamatan Gabus, sedangkan sebelah timurnya
berbatasan dengan Kecamatan Tambakromo dan sebelah selatan berbatasan dengan
Kabupaten Grobogan (Purwodadi).
JAGAD JAWA, Kabupaten Pati, memiliki sekitar 21 kecamatan, salah satunya
adalah Kecamatan Kayen. Letak kecamatan ini adalah berjarak dari pusat kota
Pati sekitar 17 Km. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sukolilo, sebelah
utara ada kabupaten Kudus dan Kecamatan Gabus, sedangkan sebelah timurnya
berbatasan dengan Kecamatan Tambakromo dan sebelah selatan berbatasan dengan
Kabupaten Grobogan (Purwodadi).Apa Itu Sesaji Bagi Orang Jawa
jujum08.00gangsaran, jagad jawa, kejawen, makna sesaji, sesaji, sesaji bagi orang jawa
Tidak ada komentar

Sesaji berasal dari kata saji.
Sajian, sesajian, maknanya sama dengan hidangan. Menyajikan berarti
menghidangkan. Sesaji kata benda bersifat tunggal, sedangkan sesajian
bermakna jamak atau plural. Sesaji yakni sesuatu yang dihidangkan.
Secara umum sesaji dibuat sebagai wujud sedekah. Saya ulangi sekali
lagi, sedekah. Sedekah yang dibagikan kepada orang lain. Sedekah
dilakukan tidak terbatas pada antar sesama manusia, melainkan bisa
dilakukan kepada bangsa tumbuhan, binatang, bahkan makhluk halus
sekalipun. Nilai esensial dari sedekah itu sendiri yakni bentuk nyata
kasih-sayang atau welas-asih antar sesama makhluk penghuni
jagad raya ini. Pemahaman ini sangat penting digarisbawahi untuk
membebaskan diri dari cengkeraman opini “sampah” yang telah mengotori
otak dan hati kita.
Secara garis besar terdapat tiga macam sesaji yang dibedakan menurut tujuan membuatnya.
Bancakan
Bancakan termasuk sesaji ditujukan untuk sedekah terutama kepada sesama manusia. Bancakan dibuat untuk dibagi-bagikan kemudian dimakan oleh orang. Untuk itu bancakan
biasanya dibuat dengan aneka rasa yang enak di lidah dan berupa
hidangan khusus yang menimbulkan selera makan. Untuk itu membuat
bancakan tidak boleh sembarangan melainkan harus dibuat senikmat mungkin
agar orang-orang yang kita sedekahi turut puas dan bahagia. Prinsipnya
sederhana saja yakni, kalau mau memberikan sedekah, maka berikan
sedekah yang sebaik-baiknya kepada orang lain. Jangan pernah berikan
“sampah” pada orang lain, yakni apa yang kita sendiri sudah enggan
memakannya.
Bancakan dibuat oleh seseorang,
kelompok, grup, atau bahkan institusi dengan berbagai tujuan misalnya
dalam rangka ritual syukuran, ritual selamatan, atau ritual doa
permohonan. Orang yang memahami kebijaksanaan hidup, saat
mengekspresikan rasa sukur tidak akan cukup hanya dengan ucapan manis di
mulut saja, tetapi mewujudkan rasa sukur itu dalam perbuatan nyata
misalnya sedekah. Doa mohon keselamatan, doa permohonan untuk
mewujudkan suatu tujuan baik, seyogyanya dibuka dengan sedekah. Karena
sedekah merupakan cara terbaik untuk memantaskan diri kita menjadi orang
yang layak menerima anugrah.
Sajèn Bebono
Sajen merupakan bahasa Jawa dari sesaji. Tetapi istilah sajen lebih familiar untuk menyebut sesaji yang bukan berupa bancakan. Bentuk sajen
biasanya tidak selalu berupa hidangan yang enak dimakan. Bahkan kadang
berupa bahan-bahan yang tidak enak dan tidak mungkin untuk dikonsumsi
oleh manusia. Misalnya minyak wangi, kemenyan, dupa, kunyit mentah,
dlingo dan bengle dll. Sajen dalam bahasa kraton lebih familiar disebut sebagai bebono
atau pengorbanan atau kurban. Akan tetapi Anda jangan membayangkan
“pengorbanan” atau “kurban” berupa tumbal setan yang menyeramkan. Anda
jangan membiasakan diri mengikuti paham “sampah” yang sering ditebarkan
melalui sinetron dan film-film murahan yang sering beredar di bioskop
dan ditayangkan televisi. Seringkali mereka membuat opini yang salah
kaprah tapi tidak menyadari hal itu telah meracuni otak masyarakat
Indonesia. Keadaan ini sungguh memprihatinkan sekali.
Sama dengan bancakan, bebono
juga merupakan sedekah. Tujuannya adalah untuk bersedekah kepada seluruh
makhluk sesama penghuni planet bumi. Sebagai manusia yang arif dan
bijaksana, manusia yang berkesadaran kosmologis, akan menyadari bahwa
hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan beragam makhluk hidup,
yang kasat mata, maupun yang tidak kasat mata. Manusia juga hidup
menumpang di antara benda-benda tidak hidup yang ada di planet bumi ini.
Dalam filsafat hidup Jawa, berpijak dari fakta-fakta itu menyadarkan
kita bahwa salah satu tujuan utama manusia hidup di planet bumi adalah
untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi di
antara makhluk hidup yang ada. Baik kepada antar sesama manusia maupun
terhadap hewan, tumbuhan, dan makhluk halus. Dalam filsafat hidup Jawa,
ditanamkan suatu kesadaran kosmologis di mana kita harus menghargai,
menghormati, dan memanfaatkan seluruh benda hidup maupun benda-benda
tidak hidup dengan cara adil, bijaksana serta penuh kasih sayang. Pada
intinya apa maksud dan tujuan dari seseorang membuat sesaji bancakan, sajen atau bebono, tidak lain untuk mewujudkan rasa menghormati, menghargai, rasa syukur dan sebagai expresi sikap welas asih
secara nyata kepada seluruh makhluk penghuni planet bumi. Dapat
dianalogikan, seperti apa yang dilakukan orang tua yang menyayangi
anak-anak tentu mereka akan bersedia mengorbankan tenaga, pikiran, beaya
dan waktu untuk membahagiakan anak-anak mereka.
Orang tua telah
memberikan bebono kepada anak-anaknya. Dalam konteks bebono,
pengorbanan atau sedekah sebagai expresi kasih sayang itu lebih
difokuskan kepada bangsa halus. Bangsa halus tidak boleh diperlakukan
semena-mena. Mereka juga makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, untuk
mengisi jagad raya ini dalam fungsinya masing-masing sesuai hukum alam
(kodrat) yang berlaku. Bangsa makhluk halus diciptakan bukan untuk
dianiaya oleh bangsa manusia, melainkan untuk berperan serta dalam tata
hukum keseimbangan alam. Sudah selayaknya bangsa manusia yang kata orang
sebagai makhluk paling sempurna, maka sempurnakan pula perilaku yang
adil dan bijaksana sebagai bagian dari bangsa makhluk hidup yang beradab
dan santun kepada alam semesta dan seluruh penghuninya.
Sajèn Pisungsung
Pisungsung artinya persembahan. Dalam konteks ini pisungsung lebih difokuskan kepada eksistensi supernatural being, misalnya ancesters atau ancient spirit
(leluhur) yakni orang-orang yang telah hidup di dimensi yang abadi.
Dalam posting saya terdahulu seringkali saya sampaikan bahwa salah satu
kunci sukses kehidupan kita adalah seberapa besar bakti kita kepada
kedua orang tua, dan para leluhur kita, hingga leluhur perintis bangsa
besar ini. Nah, pisungsung merupakan wujud ekspresi nyata bakti kita kepada para leluhur berupa suatu persembahan. Pisungsung tidak terbatas benda fisik. Bisa juga berupa persembahan melalui lisan misalnya doa, ucapan terimakasih, ucapan sembah pangabekti, hingga persembahan berupa tindakan nyata misalnya ziarah kubur, nyekar, ritual menghaturkan aneka ragam uborampe untuk pisungsung,
membersihkan pusara dst. Kita perlu mengenang para leluhur, selain
sebagai ekspresi rasa terimakasih dan hormat serta berusaha mengambil
sisi positif kehidupan masa lampau orang-orang yang telah mendahului
kita sebagai suri tauladan. Pisungsung lazimnya pula berupa
minuman dan makanan, benda-benda seperti bunga, minyak wangi yang
dulunya disukai oleh orang-orang yang mendahului kita. Atau sesuai
tradisi yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat
terhubung tali rasa sih-katresnan antara orang yang memberikan pisungsung dengan leluhur.
Sampai di sini, mudah-mudahan para
pembaca yang budiman dapat memahami dengan bijaksana. Dengan memahami
nilai luhur filsafat dalam sesaji seperti uraian di atas, diharapkan
bagi siapapun yang sedang membuat dan berbagi sesaji dapat menanamkan
pola pikir (mind set) yang tepat pula. Sehingga sesaji menjadi
lebih besar nilai filsafatnya, dan lebih efektif untuk menciptakan
perubahan positif dalam kehidupan kita. Junk opinion telah merusak nilai luhur yang terkandung dalam ritual hatur sesaji. Bahkan membeloknya esensi tujuannya. Bahkan junk opinion
telah merusak pola pikir serta mengotori kalbu pelakunya. Jika sudah
rusak pola pikirnya, kemudian orang menjadikannya sebagai alasan untuk
memojokkan dan menjelekkan tradisi hatur sesaji. Bahkan kemudian
melarangnya dengan cara menakut-nakutinya sebagai tindakan berdosa.
Entah hal ini akibat kebodohan masyarakat atau memang sebuah usaha
sistematis melakukan cultural and ethnic cleansing.
Opini Yang Dibelokkan
Untuk membantu pemahaman, saya akan
berikan beberapa contoh opini “sampah” mengenai sesaji. Yakni
pandangan-pandangan, penilaian, perspektif yang salah kaprah menyoal
sesaji.
- Sesaji dianggap sebagai bentuk “suap” atau cara untuk merayu mahluk halus, setan dsb agar bersedia membantu manusia. Ini pandangan salah yang paling popular.
- Pandangan salah berikutnya adalah, menganggap manusia yang membuat sesaji sebagai orang yang tunduk-patuh, takluk, bahkan menyembah makhluk halus. Pandangan ini lebih ngawur, makin menjauhkan dari nilai esensial yang sesungguhnya dari sesaji itu sendiri.
- Pandangan berikutnya lebih parah dan lebih ngawur. Yakni anggapan bahwa memberikan sajen akan membuat makhluk halus menjadi ketagihan dan akan menganggu jika orang tidak lagi memberikan sajen.
Baiklah para pembaca yang budiman. Saya
tetap menghargai jika ada pembaca yang bersikukuh berpendapat seperti
poin-poin di atas. Tidaklah heran jika fakta-fakta yang saya saksikan di
atas juga dianggap sebagai opini “sampah”. Itu disebabkan karena
sulitnya membuktikan fakta gaib dengan kesaksian mata kepala sendiri.
Tetapi anda juga tidak layak untuk secara subyektif merasa bahwa opini
anda paling benar dan factual.
Bagi saya pribadi dan sejauh yang bisa
saya saksikan sendiri, kenyataan di atas merupakan suatu fakta yang
jelas dan apa adanya. Walau apa yang saya saksikan sulit untuk
disaksikan pula oleh orang lain, tetapi setidaknya apa yang saya
sampaikan dapat memenuhi kaidah logika atau penalaran yang sehat.
Sesaji Sebagai Harmonisasi Dengan Alam
Sub judul di atas merupakan falsafah Jawa
tentang prinsip dasar yang melandasi tindakan seseorang untuk
memberikan sesaji atau sedekah. Tetapi akibat kurangnya pemahaman
tentang sesaji, hal itu menimbulkan stigma, yakni penilaian negative dan
pemahaman yang melenceng jauh dari prinsip dasar, pengertian, maksud
dan tujuan sesaji itu sendiri. Kadang muncul stigma sangat tendensius
yang menghakimi tindakan memberikan sesaji. Padahal dalam upacara sesaji
sesungguhnya memiliki nilai luhur kearifan local masyarakat Indonesia.
Tindakan destruktif, brutal dan tidak bertanggungjawab kadang dilakukan
sekelompok orang dengan mengatasnamakan pembelaan Tuhan. Itu terjadi
karena orang tidak tahu jika dirinya sedang tidak tahu, tidak sadar jika
dirinya sedang terbenam dalam ketidaksadaran yang sangat membius.
Seperti telah saya singgung di atas bahwa
sesaji merupakan usaha untuk berharmoni dengan hukum alam. Penjelasan
singkatnya begini, seseorang memberikan sedekah kepada beragam kehidupan
yang ada di lingkungan sekitarnya. Sedekah ini merupakan artikulasi
nyata dari kesadaran manusia untuk saling menjaga kelestarian alam,
menjaga keharmonisan dan kelangsungan ekosistem dan lingkungan hidup.
Rasa welas asih menjadi pondasi melakukan sedekah sesaji. Itu disebut pula urip (hidup) yang murup
(menyala), atau hidupnya berguna untuk seluruh kehidupan di planet
bumi. Jangankan menyakiti apalagi membunuh orang lain yang beda
pendapat, mengumpat dan meledek pun tidak dilakukannya. Perbuatan
demikian itu jelas merupakan tindakan melawan hukum alam. Cepat atau
lambat pasti akan tergulung oleh mekanisme hukum keadilan alam.
Tingkatan Sesaji
Sesaji atau sedekah jika mengacu pada
kualitasnya, sifatnya bertingkat-tingkat. Dari sesaji yang levelnya
paling sederhana (rendah) hingga paling lengkap (tinggi). Dengan
demikian, sesaji bukanlah sesuatu yang memberatkan. Tetapi dapat
disesuaikan menurut kemampuan masing-masing orang. Orang mau pilih yang
sederhana dan ringan atau yang lengkap, yang penting setiap bersedekah
atau bersesaji harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Jika terpaksa jangan
melakukannya. Efeknya pun berbeda tergantung seberapa tinggi kualitas
sesaji atau sedekah yang diberikan.
Sesaji sebagai bentuk
kebaikan pasti menimbulkan efek getaran energy positif yang memancar ke
segala penjuru. Besaran energy ini ditentukan seberapa besar kualitas
sesaji yang diberikan. Energy positif akan beresonansi kemudian
membangkitkan energy positif yang berlipat ganda, dan sebaliknya energy
negative akan meresonansi kemudian menimbulkan energy negative yang
berlipat ganda pula. Oleh sebab itu bagi siapapun yang akan memberikan
sesaji hendaknya niat dan pikiran sudah disetel secara tepat semenjak
proses membuat sesaji dimulai. Di situlah saat paling menentukan apakah
sesajinya akan menghasilkan respon positif atau malah sebaliknya.
Kuncinya terletak pada pengorbanan, persembahan, dan ketulusan yang
ditujukan kepada orang-orang, mahluk hidup dan lingkungan yang kita
hormati dan sayangi.
Demikian tadi uraian
singkat mengenai sesaji. Semoga tulisan ini dapat membantu para pembaca
yang budiman untuk memahami seluk-beluk sesaji secara proporsional dan
bijaksana.
Rahayu sagung titah dumadi
Artikel ini hanyalah hasil copas dari blog kawan, silahkan berkunjung ke tulisan aslinnya yang berjudul: Mengungkap Rahasia Sesaji (Sajen).
Foto ilustrasi adalah koleksi pribadi dan sebagian di ambil dari google dengan kata kunci SESAJI JAWA.
Makna Kalimasada Hubunganya Dengan Pancasila (Mitologi Purwa Kawitan)
Banyak orang menterjemah dan mengartikan Kalimasada adalah
kalimah sahadat, atau kalimat sahadat. Ini mungkin juga ada benarnya, alasanya
yang membuat kalimasada adalah Sunan Kalijaga. Namun belum tentu itu informasi
yang absolut dan sah, masih banyak hal-hal yang harus di bicarakan lagi,
mengenai penggunaan kalimasada itu sendiri dan si pemiliknya, serta jangan lupa
adalah tinjauan bahasa atau linguistik.
Syeh Siji Jenar Bapak Ilmu Hening Jawa
Bersamaan dengan berkembangnya masa,
kemudian terjadi keelokan dari ilmu laku yang tidak disangka-sangka.
Dikemudian hari pengetahuan pasamaden tadi muncul diterima oleh
kalangan orang Islam, sebab yakin kalau pengetahuan pasamaden tersebut
memang menjadi mustikanya keinginan dan cita-cita yang dapat
mendatangkan keselamatan, kemuliaan, ketenteraman dan hal-hal
semacamnya. Oleh karena itu pengetahuan tadi oleh orang-orang yang
sudah mendapatkan pencerahan batin yaitu Syekh Siti Jenar, yang juga
menjadi pembimbing agama Islam berpangkat wali, kemudian tercantum
didalam karya seratnya, yang kemudian disebut dengan daim, yang berasal
dari kata daiwan yang disebut diatas. Kemudian juga menjadi bagian dari
sarana manembah (penyembahan), sambil diberi tambahan julukannya,
kemudian muncul istilah shalat daim (shalat bahasa Arab, daim dari kata
daiwan bahasa Sansekerta). Adapun kemudian ditambahi istilah Arab,
hanya untuk perhatian untuk mengukuhkan keyakinan murid-muridnya yang
sudah meresapi agama Islam. Juga perkataan shalat kemudian terpilah
menjadi dua perkara. Pertama, shalat lima waktu, yang disebut shalat
Syariat, maksudnya adalah panembah lahir. Kedua, shalat daim, itu adalah
panembah batin, maksudnya adalah menekadkan (meng -I’tikadkan)
manunggalnya pribadi, atau disebut pula loroning atunggal (dua yang
menyatu [Kawula-Gusti, Ingsun-Gusti]).
Kitab karangan Syekh Siti Jenar tersebut kemudian digunakan sebagai
pokok pengajaran. Kemudian setelah mendapatkan perhatian orang banyak,
sholat lima waktu dan syara agama yang lain kemudian terpinggir, bahkan
kemudian tidak terajarkan sama sekali. Yang menjadi perhatian hanya
lelaku shalat daim saja. Maka orang jawa yang semula memeluk Islam,
apalagi yang belum, hampir semuanya berguru kepada Syekh Siti Jenar,
karena pengajarannya lebih mudah, jelas, dan nyata.
Sesudah Syekh Siti Jenar mengajarkan pengetahuan pasamaden, sebagai
teman diskusi dan bertukar pikiran adalah Ki Ageng Pengging, yang
kemudian menjadi muridnya, dikarenakan Syekh Siti Jenar adalah mitra
dalam kebaikan dari Ki Ageng Pengging, yang kemudian menjadi muridnya,
dikarenakan Syekh Siti Jenar adalah mitra dalam kebaikan dari Ki Ageng
Pengging. Pengetahuan pasamaden oleh Syekh Siti Jenar juga diajarkan
kepada Raden Watiswara, atau Pangeran Panggung, yang juga berpangkat
wali. Kemudian juga diajarkan kepada Sunan Geseng, atau Ki Cakrajaya,
yang semula bekerja menderas kelapa, (menjadi murid Sunan Kalijaga,
termasuk anggota walisanga yang ikut menyaksikan dihukum matinya Syekh
Siti Jenar, lalu berguru kepada Sunan Panggung). Asalnya dari Pagelen
(Purworejo). Kemudian ajaran tersebut menyebar diamalkan oleh orang
banyak. Demikian juga sahabat-sahabat Syekh Siti Jenar yang sudah
terbuka rasanya oleh Syekh Siti Jenar kemudian mendirikan
perguruan-perguruan pengetahuan pasamaden. Semakin lama semakin
berkembang pesat, sehingga menyuramkan pengaruh dan penguasaan agama
para wali yang sedang giat-giatnya menyerbarkan Islam syara’. Seandainya
gerakan itu dibiarkan oleh para wali, terdapat kekhawatiran masjid
akan kosong.
Pembantaian Terhadap Penganut Ajaran Syekh Siti Jenar
Agar tidak terjadi hal yang demikian, maka Ki Ageng Pengging, Syekh Siti
Jenar serta murid dan sahabatnya dijatuhi hukuman mati dengan
dipenggal lehernya, dengan perintah Sultan Demak. Demikian juga
Pangeran Panggung tidak ketinggalan, dipidana dimasukan kedalam bara
api hidup-hidup di alun-alun Demak, sebagai peringatan agar msyarakat
merasa takut, dan kalau sudah takut mereka mau membuang ajaran Syekh
Siti Jenar. Diceritakan Pangeran Panggung tidak mempan oleh amuk api,
dan kemudian melompat keluar dari dalam api, meninggalkan Demak. Sultan
Bintara dan segenap para wali terbengong-bengong dan terkagum-kagum
serta terpengaruh kewibawaan serta kesaktian Sunan Panggung, hanya
kamitenggengen ( terdiam) seperti tugu. Sesudah sementara waktu,
Pangeran Panggung sudah jauh, Sultan dan para wali baru ingat jika Sunan
Panggung sudah pergi dari tempat pidana, serta merasa kalah. Disertai
dengan banyak prajurit Sunan Geseng atau Ki Cakrajaya pergi menyusul
sunan Panggung. Sultan Demak tidak mampu menahan marah, dan melampiaskan
kemarahannya, sahabat serta murid-murid Syekh Siti Jenar yang bisa
ditangkap dibantai. Dilakukan pengejaran besar-besaran terhadap semua
orang yang dicurigai pernah mengenyam ajaran Syekh Siti Jenar. Sebagian
pengikut yang tidak tertangkap pergi meninggalkan Demak mencari
selamat.
Para sahabat dan murid yang masih hidup, masih tetap melestarikan ajaran
dan eprguruan Syekh siti Jenar tentang pengetahuan pasamaden, tetapi
kemudian dibalut dengan pengajaran syariat Islam, agar tidak diganggu
gugat oleh para wali yang menjadi alat Negara.
Ajaran Pasamaden (Olah Hening)
Adapun sebagian ajarannya adalah sebagai berikut. Pengajaran pengetahuan
pasamaden yang kemudian disebut shalat daim, dirangkapkan dengan
pengajaran shalat lima waktu serta rukun-rukun Islam yang lain-lainnya.
Pengajaran shalat daim itu disebagian kalangan disebut wiridan
(tarekat) naksyabandiyah, sedangkan lelaku pengajarannya disebut
tafakur. Sebagian ada yang dalam pengajarannya, sebelum murid menerima
pengajaran shalat daim, terlebih dahulu dilatih dengan dzikir dan wirid
membaca ayat-ayat suci. Oleh karena itu pengajaran pasamaden kemudian
terbagi menjadi dua, yaitu :
- Pengajaran pasamaden atau wewiridan dari para sabahat Syekh Siti Jenar, yang disertai dengan pengajaran syara’ rukun agama Islam. Pengajaran tadi sampai sekarang ini sudah meleset dari ajaran pokok semula, karena itu para guru sekarang, yang mempraktikan pengetahuan pasamaden, yang diberi nama (tarekat) naksabandiyah atau Syatariyah mengira bahwa pengetahuan dan wewiridan tersebut berasal dari ulama di jabalkuber (Hijaz, Mekkah). Kemudian para Kiai dan Guru tadi melaksanakan pengetahuan pasamaden menurut ajaran Jawa yang berasal dari pengajaran Syekh Siti Jenar. Atau juga para guru dan kiai tadi senang memberikan sebutan Kiniyai, yang mengandung maksud, guru yang mengajarkan ilmu setan, Sedang nama Kiai, adalah guru yang mengajarkan ilmu para nabi.
- Pengajaran pasamaden menurut Jawa, buah dari Ki Ageng Pengging, yang tadinya dipancarkan dari pengetahuan Syekh Siti Jenar (yang kemudian diberikan peraban/sebutan klenik), yaitu yang semula menjadi pembuka pengajaran, terletak pada pengelolaan perwatakan lima hal, yaitu:
- Setya Tuhu (kesetiaan dan ketaatan) atau temen (bersungguh-sungguh) dan jujur.Teguh-sentausa, adil dalam segala hal, bertanggung jawab dan tidak berkhianat.
- Benar dalam segala perilaku dan perbuatan, sabar dan berbelas kasih kepada sesama, tidak menonjolkan atau membangga-banggakan diri, jauh dari watak aniaya.
- Pandai dalam segala pengetahuan, lebih-lebih pandai dalam membuat enak perasaan sesama, ataupun juga pandai menahan dan mengendalikan rasa amarah dan jengkelnya perasaan pribadi, tidak memiliki prinsip melik nggendhong lali (kalau sudah punya dan sudah enak lupa akan asalnya), hanya karena pengaruh harta benda yang gemerlapan.
- Susila anor-raga, selalu memelihara tata karma, mengendalikan akibat penglihatan (apa yang dilihat) dan pengaruh pendengaran (pa yang didengar) kepada pihak yang terkena.
Lelaku lima hal tadi harus dilaksanakan beserta iringan puja-brata
dengan melaksanakan laku semedi, yaitu amesu cipta mengheningkan
teropong penglihatan (mubasyirah). Oleh karena itu bagi pengamalan
agama Jawa, bab mengenai pengetahuan pasamaden serta lelaku lima perkara
diatas harus diajarkan kepada semua orang, tua muda tanpa memilih
rendah tingginya derajat orang. Karena itu dengan sebab mustikanya
pengetahuan atau luhur-luhurnya kemanusiaan, ini apalagi tetap
semedi-nya, mampu menjalankan lima hal yang sudah disebutkan diatas.
Oleh karena kita tinggal disuasana ketentraman, sedangkan keadaan
tentram menyebabkan makmur-sejahtera dan kemerdekaan kita bersama. Kalau
tidak demikian, sampai rusaknya dunia, kita akan tetap menanggung
derita, papa dan terhina, tergilas oleh roda perputaran dunia, karena
kesalahan dan terkhianati oleh perasaan kita pribadi.
Praktik Ilmu Hening Cara Jawa dan Ilmu Kasunyatan
Bab pengetahuan pasamaden yang kemudian disebut Naksyabandiyah dan
Syatariyah, yang kemudian disebutkan sebagai wewiridan dari Syekh Siti
Jenar, sudah dijelaskan diatas, hanya saja aplikasinya tidak dijelaskan
secara rinci. Disini hanya akan menjelaskan lelaku aplikatif terhadap
semedi secara Jawa, yang belum terpengaruh oleh agama apapun, yaitu
seperti dibawah ini.
Para pembaca, agar jangan keliru atau salah terima, apabila ada anggapan
bahwa semedi ini menghilangkan rahsanya hidup atau nyawa (hidupnya)
keluar dari badan wadag. Penerimaan seperti itu, pada mulanya berasal
dari cerita perjalanan Sri Kresna di Dwarawati, atau sang Arjuna ketika
angraga-sukma. Agar diperhatikan, bahwa cerita seperti itu tetap hanya
sebagai persemuan atau perlambang (symbol, bukan hal atau cerita yang
sebenarnya). Adapun uraian mengenai lelaku semedi sebagai berikut.
Istilah semedi sama dengan sarasa, yaitu rasa-tunggal, maligini rasa
(berbaur berjalannya rasa), rasa jati, rasa ketika belum mengerti.
Adapun matangnya perilaku atau pengolahan (makarti) rasa disebabkan dari
pengelolaan atau pengajaran, ataupun pengalaman-pengalaman yang
terterima atau tersandang pada kehidupan keseharian. Olah rasa itulah
yang disebut pikir, muncul akibat kekuatan pengelolaan, pengajaran atau
pengalaman tadi. Pikir lalu memiliki anggapan baik dan jelek, kemudian
memunculkan tata-cara, penampilan dan sebagainya yang kemudian menjadi
kebiasaan (pakulinan /adat). Apapun anggapan baik-buruk, yang sudah
menjadi tata cara disebabkan telah menjadi kebiasaan itu, kalau buruk,
ya betul-betul buruk, dan kalau baik, ya memang baik sesungguhnya. Dan
itu semua belum tentu, karena semua itu hanyalah kebiasaan anggapan.
Adapun anggapan (penganggep), belum pasti, tetap hanya menempati
kebiasaan tata cara (adat), jadi ya bukan kesejatian dan bukan kenyataan
(real).
Apa yang dimaksudkan semedi disini, tidak ada lain kecuali hanya untuk
mengetahui kesejatian dan kasunyatan. Adapun sarananya tidak ada lagi
kecuali hanya mengetahui atau menyilahkan anggapan dari perilaku rasa,
yang disebut hilang-musnahnya papan dan tulis. Ya disitu itu tempat
beradanya rasa-jati yang nyata, yang pasti, yang melihat tanpa
ditunjukan (weruh tanpa tuduh). Adapun terlaksananya harus mengendalikan
segala sesuatunya (hawa nafsu dan amarah), disertai dengan membatasi
dan mengendalikan perilaku (perbuatan anggota badan). Pengendalian
anggota tadi, yang lebih tepat adalah dengan tidur terlentang, disertai
dengan sidhakep (tangan dilipat didada seperti takbiratul ihram, atau
seperti orang meninggal) atau tangan lurus kebawah, telapak tangan kiri
kanan menempel pada paha kiri kanan, kaki lurus, telapak kaki yang
kanan menumpang pada tapak kaki kiri. Maka hal itu kemduian disebut
dengan sidhakep suku(saluku) tunggal. Ataupun juga dengan mengendalikan
gerakan mata, yaitu yang disebut meleng. Lelaku seperti itu dilakukan
bagi yang kuasa mengendalikan gerak-bisik cipta (gagasan, ide, olah
pikir), serta mengikuti arus aliran rahsa, adapun pancer-nya (arah
pusat) penglihatan diarahkan dengan memandang pucuk hidung, keluar dari
antara kedua mata, yaitu di papasu, adapun penglihatannya dilakukan
harus dengan memejamkan kedua mata.
Selanjutnya adalah menata keluar masuknya napas, seperti berikut, Napas
ditarik dari arah pusar, digiring naik melebihi pucuk tenggorokan
hingga sampai di suhunan (ubun-ubun), kemudian ditahan beberapa saat.
Proses penggiringan atau pengaliran napas tapi ibarat memiliki rasa
mengangkat apapun, adapun kesungguhannya seperti yang kita angkat, itu
adalah mengalirnya rasa yang kita pepet dari penggiringan nafas tadi.
Kalau sudah terasa berat penyanggaan (penahanan) napas, kemudian
diturunkan secara pelan-pelan. Lelaku seperti itu yang disebut
sastra-cetha. Maksudnya sastra adalah tajamnya pengetahuan, cetha
adalah mantapnya suara dipita suara (cethak), yaitu cethak (diujung
dalam dari lidah) mulut kita. Maka disebut demikian, ketika kita
melaksanakan proses penggiringan napas melebihi dada kemudian naik lagi
melebihi cethak hingga sampai ubun-ubun. Kalau napas kita tidak
dikendalikan, jadi kalau hanya menurutkan jalannya napas sendiri, tentu
tidak bisa sampai di ubun-ubun, sebab kalau sudah sampai tenggorokan
langsung turun lagi.
Apalagi yang disebut daiwan (dawan), yang memiliki maksud :
mengendalikan keluar masuknya napas yang panjang lagipula disertai
dengan sareh (kesadaran penuh dan utuh), serta mengucapkan mantra yang
diucapkan dalam batin, yaitu ucapan “hu” disertai dengan masuknya napas,
yaitu penarikan napas dari pusar naik sampai ubun-ubun. Kemudian “Ya”
disertai dengan keluarnya nafas, yaitu turunnya nafas dari ubun-ubun
sampai pada pusar; naik turunnnya nafas tadi melebihi dada dan cethak
(pita suara). Adapun hal itu disebut sastra – cetha. Karena ketika
mengucapkan dua mantra sastra: “hu-ya”, keluarnya suara hanya dibatin
saja, juga kelihatan dari kekuatan cethak (tenggorokan). (Ucapan dan
bunyi mantra atau dua penyebutan ; “hu-ya” pada wirid Naksyabandiyah
berubah menjadi ucapan; “hu-Allah”, penyebutannya juga disertai dengan
perjalanan nafas. Adapun wiridan Syatariyah, penyebutan tadi berbunyi; [la illaha illa Allah], tetapi tanpa pengendalian perjalanan nafas.
Untuk masuk keluarnya nafas seperti tersebut diatas, satu angkatan hanya
mampu mengulangi tiga kali ulang, walau demikian, karena nafas kita
sudah tidak sampai kuat melakukan lagi, karena sudah berat rasanya (menggeh-menggeh/ngos-ngosan). Adapun kalau sudah sareh
(sadar-normal), ya bisa dilaksanakan lagi, demikian seterusnya sampai
merambah semampunya, karena semakin kuat tahan lama, semakin lebih baik.
Adapun setiap satu angkatan lelaku tadi disebut tripandurat, maksudnya
tri = tiga, pandu = Suci, rat = Jagat = Badan = Tempat. Maksudnya
adalah tiga kali nafas kita dapat menghampiri jagat besar Yang Maha
Suci bertempat didalam suhunan (yang dimintai). Yaitulah yang
dibahasakan dengan pawirong kawulo Gusti, maksudnya kalau nafas kita
pas naik, kita berketempatan Gusti, dan ketika turun, kembali menjadi
kawula. Tentang masalah ini, para pembaca hendaklah jangan salah
terima! Adapun maksud disebutnya kawula-Gusti, itu bukanlah nafas kita,
akan tetapi daya (kekuatan) cipta kita. Jadi olah semedi itu,
pokoknya kita harus menerapkan secara konsisten, membiasakan selalu
melaksanakan keluar-masuk dan naik-turunnya nafas, disertai dengan
mengheningkan penglihatan, sebab pengliahatan itu terjadi dari rahsa.
Gambar ilustrasi dari Google dengan kata kunci SYEKH SITI JENAR.
Artikel ini penulis dapat dari Blog tetangga http://gebyarmanusialangka.blogspot.com dengan judul artikel: SYEKH SITI JENAR BAPAK ILMU HENING JAWA.
Nama Hari di Jawa Adalah Nama-nama Planet
 Pernahkah berfikir tentang bagaimana sebuah nama tercipta
dan menjadi kesepakatan orang banyak? Jarang sekali terpikirkan keliatanya,
termasuk saya pribadi. Namun rasa ingin tahu saya akan sebuah kata dan asal usulnya
membuat saya terus berfikir tentang asal-usul kata tersebut dan perjalanan
sejarahnya bagaimana.
Pernahkah berfikir tentang bagaimana sebuah nama tercipta
dan menjadi kesepakatan orang banyak? Jarang sekali terpikirkan keliatanya,
termasuk saya pribadi. Namun rasa ingin tahu saya akan sebuah kata dan asal usulnya
membuat saya terus berfikir tentang asal-usul kata tersebut dan perjalanan
sejarahnya bagaimana. Satria Piningit Di Mata Saya
Ronggowarsito
adalah spiritualis indonesia yang sangat ternama karena ramalannya banyak yang
sudah terbukti. Dipaparkan ada tujuh satrio piningit yang akan muncul sebagai
tokoh yang dikemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah
“bekas” kerajaan Majapahit (Negara Indonesia), yaitu: Satrio Kinunjoro Murwa Kuncara,
Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumela Atur, Satrio
Lelono Topo Ngrame, Satrio Piningit Hamong Tuwuh, Satrio Boyong Pambukaning
Gapuro, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu.Berkenaan dengan itu, banyak kalangan
yang kemudian mencoba menafsirkan ke-tujuh Satrio Piningit itu adalah sebagai
berikut :
Jahe Jamu Kuat Pria
Jahe bagi masyarakat dipercaya dapat mengatasi kondisi mulai
dari mual, batuk, nyeri otot hingga kanker. Kemajuan ilmu medis juga telah
meneliti tentang jahe ini. Di dalam jahe ini ternyata memiliki senyawa kimia
yang bisa menimbulkan efek positif di lambung dan usus, bahkan diperkirakan
bisa meredam rasa mual dengan cara memberikan efek di otak dan system saraf.
Klambi Lurik Asli Jawa
Ngagem Lurik Karya Ki Nartosabdo
Lurik-lurik lurike weton Pedan
tur lumayan sing ngagem sajak kepranan
lurik-lurik lurike weton Trasa
nadyan prasaja sing ngagem katon gembira
Pedan Trasa lurike pancen kaloka
tuwa mudha ngagem lurik
katon endah tur ya murah
kuwi mas ndheke dhewe
mulane ja nglalekke
nengsemake nganggo weton nggone dhewe
Tari Gandrung dan Identitas Daerah
Di Banyuwangi berkembang berbagai jenis kesenian tradisional. Ada janger, kuntulan, kundaran, angklung caruk, barong, rengganis, gandrung dan masih banyak yang lain. Di antara sejumlah kesenian tradisional tersebut, gandrung menempati posisi istimewa sekaligus unik dilihat dari dinamika perkembangannya kaitan relasinya dengan negara, agama dan masyarakat.
Gandrung bagi banyak pengamat dan peneliti tak banyak beda dengan tayub, lengger, gambyong, teledek dan sejenisnya. Sebuah kesenian yang menampilkan seorang sampai empat orang perempuan dewasa menari, menembang, sendirian maupun berpasangan dengan penonton pria (pemaju) pada malam hari dengan iringan orkestra sederhana; gong, kethuk, keluncing (trianggel), biola, kendang. Namun bagi para tokoh di Banyuwangi gandrung tidak sekedar kesenian profan sekedar bersenang-senang menghabiskan malam, tapi sebuah kesenian yang sarat dengan nilai historis dan kepahlawanan.
Kesadaran sejarah atau barangkali lebih tepatnya romantisme historis ini berkembang pada awal tahun 70-an setelah beberapa budayawan mencoba memberikan tafsiran makna dari gending-gending klasik yang dibawakan gandrung seperti gending padha nonton, sekar jenang, seblang lokinto, layar kumendhung dan lain-lain. Kemudian ditambah diperolehnya beberapa dokumen tulisan lawas penulis Belanda dan beberapa tulisan berbahasa Inggris yang membantu upaya penggalian makna tersebut. Berdasar hasil tafsiran makna gending-gending klasik tersebut lahir wacana bahwa gandrung adalah sebuah kesenian yang berfungsi sebagai alat perjuangan melawan Belanda. Analisanya begini; setelah Perang Puputan Bayu pada tahun 1771-1772 rakyat Blambangan yang hampir habis dan sisanya tinggal memencar dalam kelompok-kelompok kecil di pedalaman hutan, maka untuk konsolidasi perjuangan dan membangkitkan lagi semangat juang lahirlah kesenian gandrung yang berkeliling menghubungi sisa-sisa pejuang yang terpencar tadi.
Kesimpulan ini berdasar tulisan John Scholte dalam Gandroeng van Banjoewangi tahun 1926. Sebenarnya tulisan Scholte ini tidak memberikan data yang cukup jelas. Keyakinan fungsi perjuangan kesenian gandrung sebenarnya lebih bertumpu pada hasil pemaknaan terhadap syair-syair klasik. Wacana gandrung sebagai alat perjuangan ini kemudian berkembang menjadi keyakinan dan kesadaran kolektif di kalangan tokoh-tokoh di Banyuwangi. Hal ini terlihat pada tulisan-tulisan yang terbit di Banyuwangi seperti buku “Gandrung Banyuwangi” yang diterbitkan oleh DKB (Dewan Kesenian Blambangan) tanpa tahun, artikel di majalah Seblang edisi II tahun 2004 yang berjudul “Gandrung Kawitane Alat Perjuwangan” dan banyak tulisan lain yang diangkat di media lokal maupun nasional.
Kesadaran sejarah peran gandrung berjalan seiring dengan upaya pencarian identitas daerah yang mulai giat dilakukan Pemda sejak awal tahun 70-an. Gandrung sebagai kesenian masyarakat Using yang dianggap sebagai masyarakat asli Banyuwangi menjadi pilihan yang paling gampang dari pada kesenian-kesenian lainnya. Selain alasan-alasan estetika, misalnya dari segi performance gandrung pasti lebih menarik dibanding angklung caruk yang seluruh pemainnya laki-laki, gandrung juga lebih populer dibanding kesenian-kesenian lainnya. Maka jadilah gandrung yang awalnya hanya dikenal di lingkungan masyarakat petani, perkebunan, nelayan yang erat dengan ritual, ditarik oleh negara menjadi identitas daerah yang sepenuhnya profan.
Tahun 1975 lahirlah koreografi baru tari “Jejer Gandrung“ sebagai tari selamat datang yang digelar untuk acara-acara formal menyambut tamu negara. Sebuah tari yang mencoba merangkum seni pertunjukan gandrung yang terdiri dari babak jejer, paju dan seblang subuh yang dipentaskan semalam suntuk, diringkas hanya dalam durasi waktu 15 menit. Sebagai identitas, negara punya ukuran estetika sendiri yang ketat baik penari maupun panjak (penabuh gamelan) dan pelengkap performance lainnya. Dari sinilah kemudian gandrung sebagai kesenian memiliki dua basis pendukung, yaitu gandrung di komunitas awalnya yaitu gandrung terob dan gandrung sanggar. Gandrung terob adalah komunitas seniman kesenian gandrung dan masyarakat pendukungnya. Sedangkan gandrung sanggar adalah komunitas seniman yang menyuplai pementasan formal yang diminta negara.
Gandrung sebagai identitas bagi Banyuwangi yang multi etnik tidak selalu berada dalam satu kata. Gandrung berada dalam posisi tarik ulur dan diperdebatkan oleh kekuatan yang melingkarinya. Kekuatan tidak hanya dalam pengertian negara atau pemerintah daerah, melainkan juga wacana dominan dan nilai-nilai yang disepakati masyarakat. Dalam hal ini agamawan dengan teksnya sendiri soal ukuran-ukuran moral, budayawan dengan teksnya sendiri yaitu gandrung sebagai warisan sejarah yang luhur, negara dengan teksnya sendiri gandrung sebagai alat negara, semuanya berebut dan berpilin dengan kekuatannya masing-masing. Sedangkan komunitas gandrung terob tidak tahu menahu dan berada di luar kontestasi ini. Mereka berada dalam posisi yang dibaca.
Pergulatan ini berjalan intens walau tidak selalu secara terbuka. Kasus dibongkarnya patung gandrung di pelabuhan Ketapang atas permintaan kaum agamawan Ketapang menunjukkan hal itu. Dalam kasus ini melibatkan juga anggota DPRD yang harus turun meninjau dan menindaklanjuti pengaduan keberatan masyarakat atas adanya patung gandrung yang berada tepat di depan masjid walau sebenarnya masih dalam area pelabuhan. Namun peran dominan negara dan wacana identitas daerah mengalahkan wacana-wacana kontra. Di tengah polemik gandrung sebagai identitas Banyuwangi di sidang-sidang DPRD, pada tahun 2003 keluar SK bupati nomor 147 yang menetapkan tari jejer gandrung sebagai tari selamat datang di kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian pemihakan terhadap gandrung yang bersifat politis menimbulkan akibat politis pula. Akibatnya ketika didirikan pusat latihan gandrung di desa Kemiren, program ini hanya berlangsung dua tahun karena pada tahun berikutnya anggarannya tidak disetujui oleh DPRD.
Di tangan negara, gandrung sebagai identitas daerah menjadi wacana dominan. Patung dan gambar gandrung menghiasai kota dan desa. Gambar gandrung menghias tempat sampah, pot bunga di trotoar, brosur pariwisata, baliho di perempatan jalan dan dinding perkantoran. Patung gandrung diletakkan di sudut-sudut taman, gapura kampung sampai pintu masuk kabupaten. Bahkan di pintu masuk dari utara di wana wisata Watu Dodol dibangun patung gandrung setinggi 12 m. Begitulah gandrung telah direngkuh negara dan karena menjadi identitas menghendaki tunggal, maka gandrung sebagai sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dinilai semakin berada di tempat tinggi dan semakin kentara untuk diperdebatkan dan diperebutkan.
Setelah gandrung menjadi identitas daerah, menjadi taruhan image daerah, maka Pemda menerapkan standar estetika yang memenuhi unsur kepantasan laik jual dan membanggakan. Pada saat demikianlah kemudian ketika negara mengirimkan muhibah seni baik nasional maupun internasional terjadi proses marjinalisasi secara sistematis. Yang dipilih mewakili negara bukanlah komunitas gandrung terob melainkan gandrung sanggar yang lebih mampu memenuhi standar estetika yang ditetapkan negara. Disaat gandrung menjadi kebanggaan kolektif, justru komunitas aslinya termarjinalkan. Mereka tidak mempunyai kemampuan dan keberanian untuk berbicara, mereka lebih menganggapnya sebagai problem yang tak terucapkan.
Belum lagi problem relasinya dengan agama. Dengan semakin intensifnya proses purifikasi agama menempatkan gandrung berada pada posisi pesakitan. Gandrung distigma sebagai kesenian maksiyat dan tidak layak didekati. Konstruk agama dengan dengan seperangkat standar moralitas telah mereduksi estetika pertunjukan gandrung. Goyang pinggul, minuman keras, berbaurnya laki-laki dengan perempuan, kostum semuanya bertentangan dengan nilai dominan yang dikembangkan agama. Sekali lagi gandrung berada pada posisi yang lemah, sebagai pihak yang dinilai. Walau mereka sebenarnya memiliki ukuran nilai sendiri namun sekali lagi tak terucap dengan lantang. Mereka dalam posisi bertahan dan sering kali secara tak sadar menerima setigma dari luar sebagai kebenaran.
Dalam kaitan membangun tata sosial yang berkeadilan, memberikan kesempatan yang sama terhadap semua elemen masyarakat untuk berekspresi tanpa tekanan dari pihak lain, ketidakseimbangan relasi ini perlu diupayakan agar terjadi relasi yang seimbang antara komunitas gandrung terob dengan kekuatan dominan yang melingkupinya. Mereka diberdayakan agar mampu berfikir secara kritis membaca posisinya sendiri di tengah relasinya dengan kelompok lain. Membangun kemampuan mereka untuk menyadari dan berani menyuarakan kemarjinalannya, dan mampu mengevaluasi kekurangan mereka sendiri sangat penting dalam kerangka berfikir bahwa perubahan sosial akan menjadi lebih sehat dan memiliki daya perlawanan yang kuat apabila tumbuh dari komunitas itu sendiri. Bukan perubahan yang dibangun dari atau oleh pihak luar akan tetapi tumbuh dari kesadaran mereka sendiri.
Di Tulis oleh Pak Hasan Basri dari Banyuwangi. Kunjungi blognya untuk mendapatkan berita lebih banyak tentang Banyuwangi. Hasan Basri BLOG.
Sinden di Ambang Kehancuran
Hal yang cukup 'mencengangkan' sekaligus juga menggembirakan saat
Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Semarang (Unnes),
Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unnes, dan Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI) Jateng akan menggelar acara kompetisi bertajuk “Sinden Idol 2012”.
Pendaftaran dan penjaringannya dibuka pada 15 Oktober-15 November 2012
mendatang. Sebuah ajang pencarian sinden-sinden berbakat di Jawa
Tengah. Tak main-main hadiahnya sangat menggiurkan. Untuk pemenang
pertama mendapatkan 20 juta, kedua 15 juta dan ketiga 10 juta.
Sinden sendiri berarti vokal tunggal yang (kebanyakan) dibawakan oleh
wanita. Namun, agak berbeda pengertian sinden dengan vokalis dalam
musik pada umumnya. Sinden bukanlah vokalis. Vokalis adalah orang yang
bernyanyi dan diiringi dengan instrumen musik. Vokalis menjadi pusat
perhatian karena tema dan pesan utama tertampung dalam balutan
lirik-liriknya. Dengan demikian, vokalis menjadi acuan dalam sebuah
pertunjukan musik. Sementara pengertian sinden tidak demikian. Kedudukan
sinden setara dengan instrumen gamelan lain. Tidak mencoba diiringi
maupun mengiringi. Singkatnya, sinden juga dianggap sebagai satu
kesatuan instrumen gamelan. Agar terwujudnya capaian rasa gending yang
ideal, maka semua instrumen harus saling bersinergi antara satu dengan
yang lain, tak terkecuali sinden.
Warna Lain
Susan Pratt Walton dalam disertasinya yang berjudul “Heavenly Nymphs
and Earthy Delights: Javanese Female Singers, Their Music and Their
Lives” (1996) dengan lugas menyatakan, walaupun suara sinden lebih
terdengar nyaring daripada instrumen gamelan lainnya tapi bukan berarti
ia menjadi panutan dan dasar acuan. Karena dalam hampir keutuhan
sajian, sinden tidak berperan sebagai pemimpin bagi keseluruhan
ansambel layaknya vokalis dalam orkestra musik Barat. Namun, sinden
menjadi begitu istimewa karena boleh dikata ialah satu-satunya yang
memberi ‘warna lain’ dalam pertunjukan karawitan. Bukan karena apa yang
disajikan, namun oleh siapa yang melagukannya. Membicarakan sinden
berarti membicarakan gender –jenis kelamin-. Ya! Sinden adalah wanita
yang kadang memberi guratan nuansa lain dalam ingar-bingar kuasa
laki-laki atas gamelan.
Bukan satu hal yang aneh, fenomena tergusurnya wanita dalam jagat
“musik tradisi” kita sudah lama diberlangsungkan. Kuasa laki-laki masih
sangat dominan. Musik-musik tradisi Nusantara dan khususnya Jawa
menempatkan supremasinya sebagai satu dari sekian banyak olah kebudayaan
yang memiliki wajah dan jiwa kekerasan kalau bukannya kelelakian.
Wanita hanya menjadi simbol yang mengguratkan aura feminisitas sehingga
kehadirannya kadang dianggap kurang layak jika menghuni ruang-ruang
dengan imaji yang maskulin. Wanita mengalami kebangkrutan eksistensi
dalam jagat musik tradisi di Jawa. Adanya sinden seolah memberi oasis
yang menyegarkan bagi denyut hidup wanita dalam musik tradisi terutama
karawitan Jawa.
Apa yang unik dari (pe)sinden? Pertama, lihatlah posisi duduknya, mereka bersimpuh dalam balutan kain jarik
dengan posisi punggung yang tegak. Tak cukup dengan hanya hitungan
menit, namun jam. Bahkan semalam suntuk mereka harus duduk dengan posisi
demikian untuk menemani sang dalang mempergelarkan pertunjukan wayang
kulit. Adakalanya terjadi interaksi yang harmonis antara sinden dan
dalang. Sinden tak dibekali ruang untuk berolah tubuh layaknya
penyanyi-penyanyi lain di abad ini. Kuasa sinden tak dilihat dalam
domain fisiknya, namun olah dan kemerduan vokalnya. Jangan heran
kemudian jika sinden-sinden idola dari masa ke masa bertubuh bongsor
namun memiliki dentuman suara yang mampu memikat hati kaum adam.
Era Narto Sabdo -dalang kondang-, banyak mengubah citra sinden di mata
masyarakat. Sinden, tidak lagi harus duduk di belakang dalang. Sinden
kemudian berada di samping kanan sang dalang, namun bertolak belakang
arah hadap. Sinden secara langsung menjadi etalase bagi mata penonton.
Dengan arah hadap yang demikian, mengharuskan para pesinden untuk
tampil cantik dan menawan. Era suara kemudian harus diimbangi dengan
citra visual. Walhasil, banyak sinden yang kemudian merawat tubuhnya
untuk tampil ‘seseksi’ mungkin dengan dandanan yang menor.
Kedua, seorang sinden harus memiliki penguasaan bekal musikal yang
mumpuni. Pesinden berada dalam pusaran tafsir dan imajinasi musikal
tinggi. Karenanya, tak semua vokalis wanita mampu menjadi pesinden. Ia
harus sadar betul cara mengornamentasi sebuah gending dengan tafsir teks
(cakepan), irama, rasa, tempo dan tentu saja garap. Sinden
yang handal berarti telah qatam akan semua itu. Seorang sinden diuji
bukan dari kualitas suara semata, namun kesatuan yang terjalin dengan
gending yang dibawakan. Oleh karena itu, pesinden berbeda dengan
penembang. Disebut sinden karena kehadirannya yang menyertai sebuah
gending walaupun teks vokal yang disajikan adakalanya berupa tembang.
Sementara penembang bisa melagukan vokal secara mandiri tanpa adanya
(iringan) gending gamelan. Singkatnya, pesinden sudah pasti penembang,
namun penembang bukan berarti seorang pesinden. Hal ini wajib diketahui
agar keduanya tidak saling silang pengertian.
Kompetisi
Sinden Idol 2012 seolah berusaha memberikan sejumlah tawaran alternatif
akan pemikiran dan generasi penerus sinden di Jawa pada umumnya.
Diharapkan, kompetisi ini mampu memunculkan dan sekaligus mencetak
generasi baru sinden yang bermutu. Mengembalikan kodrat sinden dalam
takaran penilaian auditif (suara) bukan lagi glamournya visual yang
selama ini banyak menghiasi wajah pertunjukan wayang kulit muthakir.
Namun sayang, ada beberapa catatan yang kurang diperhatikan dalam
kompetisi itu.
Dari press release di media serta informasi yang didapat
dari website Unnes, tak ada batasan usia bagi peserta. Hal ini
mengingatkan jenis kompetisi serupa yang beberapa waktu lalu (September)
diberlangsungkan di ISI Yogyakarta dalam mencari sosok pemain
-instrumen- gender berbakat. Tak ada batasan usia. Peserta terdiri dari
para empu gender di Jawa Tengah dan Yogya. Bahkan tim penilai konon
adalah anak didiknya, kalah senior. Akibatnya, hampir semua pemenang
adalah generasi penggender yang sudah dikenal publik. Tak satupun
peserta muda yang mendapatkan nomor di ajang itu.
Bisa jadi pula, banyak pesinden yang sudah mahsyur dan ternama akan
mengikuti lomba Sinden Idol 2012. Jika demikian ambisi dalam mencari
bibit-bibit sinden baru akan mengalami kebuntuan. Karena tak diragukan
lagi, para senior sinden tersebut telah teruji di mata masyarakat,
sehingga menjadi tabu jika dipersaingan itu ia kalah. Di sisi lain,
batasan wilayah sindenan juga tidak dijelaskan secara spesifik, hanya
berkisar pada gaya Jawa Tengahan. Padahal kita tahu, sindenan banyak
variasi dan gayanya. Ada versi Surakarta, Semarangan, Sragenan, bahkan
Banyumas dan Tegal. Suraji dalam tesisnya yang berjudul “Sindenan Gaya
Surakarta” (2005) mencirikan dengan spesifik gaya sindenan Surakarta
dibanding dengan lainnya. Bahkan di wilayah Surakarta sendiri banyak
ragam dan versi yang tidak bisa dikomparasi baik buruk antar satu dengan
lainnya.
Pertanyaannya kemudian bagaimana jika peserta Sinden Idol 2012
membawakan sinden dengan versi yang beraneka ragam tersebut? Satu sinden
memiliki citra penilaian yang berbeda. Bisa jadi, apa yang dianggap
bagus bagi gaya A adalah sepele di gaya B, atau sebaliknya. Sampai di
sini, batasan dan kriteria penilaian harus lebih dapat diperjelas. Hal
itu menjadi “pekerjaan rumah” bagi panitia. Walaupun demikian, Sinden
Idol 2012 patut untuk diapresiasi sebagai sebuah langkah kongkrit
institusi, terkait pembelaan terhadap kesenian tradisi. Karena bukan
rahasia lagi, denyut hidup kesenian tradisi dewasa ini semakin tak mampu
menunjukkan detaknya. Tertimbun dalam tumpukan jerami seni-seni
populis yang glamour dan gemerlap.
Ditulis oleh Aris Setiawan (Dosen ISI Surakarta), pernah diterbitkan di harian Suara Merdeka, 3 November 2012.
Gambar dari browsing di Mbah Google dengan kata kunci "Sinden".
Sanggit dan Kinerjanya
Sanggit sudah tidak asing lagi bagi
telinga penggemar wayang, yang bisa diartikan sebagai ciri khas seorang
dalang dalam membawakan cerita tertentu. Dalang A dan dalang B dalam
sajiannya akan berbeda meskipun mereka menyajikan satu lakon. Kadang
juga dalang A dalam membawakan lakon yang sama tetapi dipentaskan
beberapa kali ditempat yang berbeda juga akan berbeda dalam sajiannya.
Karena memang pertunjukan wayang itu sangat kontekstual. Tulisan ini
hanya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa itu sanggit dan
bagaimana menyusun sanggit yang baik. Tentunya ini merupakan salah satu
alternatif atau sebagai penawaran sistem kerja bagi seorang dalang
ataupun calon dalang.
Nah sebagai ilustrasi saya sisipkan
tembang macapat Megatruh yang terdapat dalam Serat Sabdajati karangan
Ranggawarsita. Untuk mengetahui lebih detail tentang serat ini anda bisa
berkunjung (klick aja di sini).
Haywa pegat ngudia ronging budyayu,
margane suka basuki,
dimen luwa kang kinayun,
kalis ing panggawe sisip,
ingkang taberi prihatos.
Ulatana kang nganti bisa kapangguh,
galedhagen kang sayekti,
talitinen aywa kleru,
larasen sajroning urip,
den tumanggap dimen manggon.
Panggonane aneng pangesthi rahayu,angayomi ing tyas wening,
eninging ati kang suwung,
nanging sejatine isi,
isine cipta kang yektos.
Lakonana kalawan sabaring kalbu,
yen den obah neniwasi,
kasusupan setan gundhul,
ambebedhung nggawa kandhi,
isine rupiyah keton.
Perkembangan jaman menuntut
kreatifitas seorang dalang sebagai pelaku seni dalam pertunjukkan
wayang. Kreatifitas adalah merupakan sistem atau cara kerja dalang, maka
kreatifitas dapat dibagi menjadi dua bagian, dalam hal ini Jlitheng
Suparman berpendapat bahwa secara sistematik, wujud kreativitas dalang
terdiri dari dua dimensi: konsep dan implementasi konsep. Sanggit adalah
konsep yang disusun di bawah panggung berupa teks (balungan lakon dan
atau naskah). Implementasi konsep adalah tafsir teks dalam bentuk sajian
yang disebut “cak pakeliran” Bangunan teks (sanggit
atau konsep cerita/lakon) atau disebut struktur cerita terdiri dari
unsur-unsur substansial berupa tema, amanat, alur/plot, setting, dan
penokohan. Implementasi teks atau sanggit disebut “cak pakeliran” yakni
penyajian atau tafsir sanggit melalui perangkat ekspresi berupa: catur,
sabet dan gendhing. Pengolahan dari ketiga perangkat ekspresi tersebut
menghasilkan sebuah nuansa ekspresi berupa: sem, nges, greget, dan regu.
Lebih jelasnya bahwa sanggit merupakan
salah satu kinerja dalang dalam menyusun sebuah naskah (naskah wayang).
Naskah ini bisa berbentuk balungan lakon atau naskah utuh. Balungan
lakon hanya terdiri dari struktur adegan atau plot-plotnya, sedangkan
naskah utuh adalah sudah menjelaskan sajiannya secara menyeluruh.
Artinya sanggit merupakan langkah awal dalang sebelum melakukan
pementasan. Menurut pemikiran saya dengan adanya sanggit, maka akan
tercipta (timbul) ilustrasi untuk musik dan sabet. Artinya sanggit
merupakan elemen dari totalitas pertunjukan wayang tersebut. Dengan
sanggit kemudian musik bisa berbicara dengan mediumnya yang sifatnya
memberikan ilustrasi baik dengan mengkaji penokohan (pengkharakteran)
atau suasana adegan yang diharapkan. Dalang bisa menciptakan stayle
sabet yang sesuai dengan sanggit yang dibuat. Mungkin juga bisa disebut
sanggit merupakan kunci dari sistematis pertunjukan wayang. Oleh karena
sanggit merupakan elemen dari keseluruhan sajian, maka dalam pembuatan
sanggit sangat perlu perenungan-perenungan secara matang, dengan
memperhatikan alur cerita, dramatikalnya dan setting atau situasi.
- Daya imajinasi adalah lebih dikarenakan cerita wayang itu bersifat fiktif atau khayalan. Bukan sekedar mensitir kisah nyata, tetapi lebih dalam keliaran berfikir khayalan, sehingga tidak nampak atau semu, perbandingannya adalah wartawan yang tukang cari kabar, dia hanya menggaris bawahi kabar tersebut. Wah bagus ini kalau soal berkhayal, aku paling hobi, berkhayal punya cewek, ha ha ha.
- Kepekaan intuisi adalah kepekaan rasa dan nalar kita terhadap peristiwa-peristiwa sekeliling kita kekinian sehingga realitas itu menjadi materi tematik maupan sebagai muatan kisah nantinya. Kepekaan intuisi ini bisa dicapai kalau jaman nenek moyang dahulu dengan cara laku brata. Apakah cara-cara seperti itu masih relevan dengan situasi sekarang? Itu tergantung kedewasaan masing-masing individu dalang. Menurut saya pribadi bahwa dengan cara banyak membaca, menggunakan berbagai media untuk mencari informasi itu adalah salah satu langkah yang bagus di era komunikasi seperti sekarang ini. Toh semua sudah dibahas, semua sudah ditulis, kita tinggal belajar dan memahami saja. Budayakan browsing di google atau yahoo dan cari reverensi di wikipedia dan lain sebagainya.
- Intelektualitas adalah khasanah ilmu pengetahuan, kemampuan analisis persoalan dan kamampuan meramu antara pembayangan, realitas kekinian dan materi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan khasanah cerita wayang yang ada. Intelektualitas adalah khasanah ilmu pengetahuan, kemampuan analisis persoalan dan kamampuan meramu antara pembayangan, realitas kekinian dan materi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan khasanah cerita wayang yang ada. Jika tiga instrumen tersebut berjalan maka akan terumuskan sebuah sanggit yang secara struktural berkualitas/menarik dan kontekstual.
Toh jaman dulu nenek moyang kita sudah terkenal dengan ndregilnya atau pinter ngothak-athik
(tentunya dengan berbagai pertimbangan), sehingga Mahabarata dan
Ramayana yang ada sekarang berbeda dengan sumber aslinya secara alur
cerita. Karena terdapat penambahan-penambahan di sana sini yang tentunya
penambahan tersebut sesuai dengan situasi jamannya. Istiliahnya
kendregilah simbah-simbah karena memang mereka peka terhadap situasi
jamannya, tidak hanya menggunakan sebuah dogma begitu saja, tetapi lebih
dititik beratkan pada pengkawinan antara dogma yang datang dengan
tradisi lokal, sehingga tercipta sebuah bentuk baru.
Dari pendapat tersebut jelas bahwa cara
kerja dalang meliputi pra pertunjukan dan pertunjukan itu sendiri.
Pembentukan konsep pertunjukan yang berhubungan dengan sanggit sangat
membutuhkan kepekaan bagi seorang dalang dalam menanggapi fenomena yang
sedang terjadi di masyarakat. Alhasil seorang dalang harus senantiasa
belajar, memahami dan menyimpulkannya. Sehingga terbentuk sebuah konsep
baru yang memadai dan mampu memberikan pencerahan terhadap para
penggemar wayang. Dengan demikian pasti wayang selalu di gemari oleh
masyarakat pendukungnya dan tetap eksis. Mangga teman-teman calon dalang
berlatih dan belajar bersama yuk.
Hasil Diskusi Bersama, di rangkum oleh Rencansih